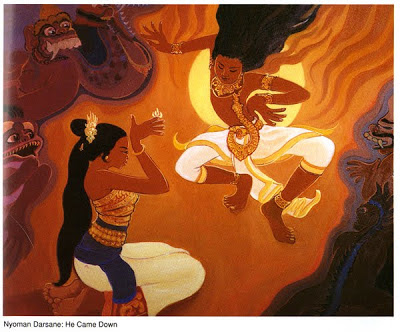Pada 14 Maret 2018, Prof. Stephen Hawking, Ph.D., telah wafat dalam usia 76 tahun. Dia menanggung dengan kalem penyakit ALS sejak 1963 yang membuatnya lumpuh total, tapi tetap mampu menghasilkan sekian buku yang laku keras dan berkomunikasi lisan lewat synthesizer suara.
Hidupnya telah berakhir. Abu jasad Stephen Hawking disimpan di Gereja Anglikan Westminster Abbey, London, Inggris.
Tapi warisan pemikirannya dalam fisika dan kosmologi teoretis akan bertahan lama bahkan mungkin abadi. Inilah
transhistorical eternity atau
historical transcendence, bergantung anda melihatnya dari kacamata apa.
Tulisan ini menyoroti beberapa segi pemikiran Stephen Hawking sebagai seorang pemikir besar di dunia fisika teoretis abad ke-20/21. Supaya lengkap, pemikiran Albert Einstein juga akan disajikan, tentu saja hanya segi-segi tertentunya.
Mari kita mulai dengan Stephen Hawking.
Kaum agamawan umumnya suka memakai contoh diri mahafisikawan Stephen Hawking (lahir 8 Januari 1942) sebagai seorang ateis yang terkena kutuk Tuhan. Kata kaum agamawan, “Lihatlah, barangsiapa ateis, dia akan terkena kutuk Tuhan, seperti diri Stephen Hawking yang dibuat lumpuh total. Sudah sejak awal Tuhan tahu kalau Hawking akan jadi ateis. Maka itu, dia dijadikan lumpuh.”
Ya, Stephen Hawking di tahun 2004 saat ditanya oleh seorang wartawan
The New York Times apakah dia percaya Allah, pendek saja dia menjawab, “Aku tidak percaya pada suatu Allah personal.”/1/
Dalam video Discovery Channel
Curiosity S01E01 yang berjudul
Did God Create the Universe? Compelling Explanations, yang ditayangkan premier 7 Agustus 2011, Hawking menyatakan hal berikut ini:
“Aku percaya, penjelasan yang paling sederhana adalah tidak ada Allah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta dan tidak ada yang mengarahkan nasib kita. Ini membawa aku ke suatu kesadaran yang sangat dalam bahwa mungkin sekali juga tidak ada sorga dan tidak ada kehidupan setelah kematian juga. Kita punya satu kehidupan saja untuk menghargai dan mengagumi Desain Akbar jagat raya, dan untuk itu aku sangat bersyukur.”/2/
Baru-baru ini dengan tegas dan jelas di muka umum Hawking menyatakan kembali dirinya ateis. Saat diwawancara oleh koran Spanyol
El Mundo (dipublikasi 26 Oktober 2014), sang mahafisikawan ini menyatakan,
“Sebelum kita memahami sains, adalah hal yang wajar untuk percaya bahwa Allah telah menciptakan alam semesta. Tapi kini sains mengajukan sebuah penjelasan yang lebih meyakinkan. Apa yang dulu saya maksudkan dengan ‘kita akan tahu pikiran Allah’ [dalam buku A Brief History of Time, terbit 1998] adalah bahwa kita akan ketahui segala sesuatu yang Allah tahu [sebagai the theory of everything], seandainya Allah ada, tapi faktanya dia tidak ada. Saya kini seorang ateis.”/3/
Ihwal mengapa sains tidak memerlukan sosok Allah supernatural dalam terjadinya jagat raya, dijelaskan oleh Hawking dalam video Discovery Channel yang berjudul
Did God Create the Universe? yang sudah dirujuk di atas. Antara lain dia menyatakan hal berikut ini:
“Peran yang dimainkan sang waktu pada permulaan jagat raya adalah, aku percaya, kunci terakhir untuk menyingkirkan keperluan adanya suatu Perancang Akbar [ilahi], dan untuk menyingkapkan bagaimana jagat raya menciptakan dirinya sendiri [lewat fluktuasi quantum]…. Waktu itu sendiri haruslah akhirnya berakhir. Anda tidak dapat tiba di suatu waktu sebelum big bang, karena tidak ada sang waktu sebelum big bang.
Kita akhirnya menemukan sesuatu yang tidak memiliki suatu penyebab karena tidak ada waktu bagi suatu penyebab untuk ada di dalamnya. Bagiku, ini berarti tidak ada kemungkinan bagi adanya suatu pencipta [ilahi] berhubung tidak ada waktu bagi suatu pencipta untuk dulu ada. Karena waktu itu sendiri dimulai pada momen big bang, maka big bang itu sendiri adalah suatu kejadian yang tidak dapat disebabkan atau diciptakan oleh seseorang atau suatu hal apapun….
Maka, ketika orang bertanya kepadaku apakah suatu allah telah menciptakan jagat raya, aku katakan kepada mereka bahwa pertanyaan anda itu sendiri tidak punya makna. Waktu belum ada sebelum big bang, dengan demikian tidak ada waktu bagi Allah untuk membuat jagat raya di dalamnya. Ini bak bertanya arah menuju pinggir Bumi. Planet Bumi itu suatu bulatan. Sebagai bulatan, Bumi tidak punya suatu tepi, alhasil mencari tepi Bumi adalah suatu usaha yang sia-sia.”/4/
OK-lah, para agamawan tentu bebas menilai Stephen Hawking. Tapi apa komentar saya terhadap kaum agamawan yang berpendapat demikian keras tentang diri Stephen Hawking?
Pertama, jika Stephen Hawking jadi lumpuh total karena dia dikutuk Tuhan, karena dia ateis, maka, menurut saya, betapa kejamnya Allah kaum agamawan.
Jika anda membutuhkan teologi tentang Allah yang kejam, ingatlah bahwa teologi anda adalah juga psikologi anda yang sebenarnya: anda sendirilah yang sebenarnya berjiwa kejam, bukan Allah manapun.
Seandainya Allah yang kejam semacam ini ada, Allah ini bukan hanya kejam, tetapi juga tidak mau ilmu pengetahuan berkembang, lewat pikiran Hawking, dalam dunia manusia. Allah semacam ini kejam dan anti-sains, atau karena anti-sains, Allah ini jadi kejam.
Hemat saya, Allah dalam agama-agama besar bukanlah Allah yang kejam semacam itu.
Semakin anda yakin bahwa Allah anda itu Allah yang mahatahu, hemat saya pastilah dia Allah yang, seperti semua orangtua kepada anak-anak mereka, juga menghendaki anda semua bertumbuh untuk menjadi serbatahu seperti dirinya dengan belajar dan meraih ilmu pengetahuan seumur kehidupan anda dan dengan tanpa batas.
Kedua, meskipun tubuhnya lumpuh total karena serangan berkelanjutan penyakit neuron motoris yang berhubungan dengan penyakit
sclerosis lateral amyotrofik (ALS) sejak dia berusia 21 tahun, semangat hidupnya tidak mati dan pikirannya tidak lumpuh.
Kenyataan seperti itu pada diri Stephen Hawking menunjukkan dia tidak dikalahkan oleh Allah kaum agamawan yang kata mereka telah mengutuknya.
Bahwa Hawking terkena sakit semacam ini, memperlihatkan dirinya sama dengan manusia lain, bisa terkena penyakit, bukan karena dia berdosa terhadap Tuhan apapun.
Tentu saja, sebagai seorang manusia, Hawking mengakui bahwa dia terpukul juga oleh apa yang dideritanya. Kepada wartawan
The New York Times yang mewawancarainya di tahun 2004, dia menyatakan,
“Harapan-harapanku lenyap saat aku berusia 21 tahun. Sejak waktu itu, segala sesuatu adalah sebuah bonus.”
Tetapi kendatipun demikian, hingga saat ini Hawking mampu menikmati kehidupannya. Baginya, banyak hal yang lucu dan menarik dari kehidupan ini. Katanya kepada wartawan yang sama, “Kehidupan ini akan jadi tragis seandainya kehidupan ini tidak lucu.”/5/
Ketiga, dalam kenyataannya Stephen Hawking, meskipun lumpuh, lebih hebat dan lebih berprestasi dibandingkan anda yang sehat jasmaniah.
Meskipun dia secara bertahap menjadi lumpuh total, sekian buku berkualitas best seller telah ditulisnya lewat pikirannya yang brillian. Teknologi modern telah membantu Stephen Hawking melampaui kelumpuhannya sehingga dia bisa berbicara dan tetap produktif menulis.
Ya, Hawking tetap seorang bebas; katanya lisan dalam sebuah video di Youtube,
“Walau saya tidak dapat bergerak dan saya harus berbicara lewat sebuah komputer, dalam pikiran saya, saya seorang bebas.”/6/
Ya, hemat saya, walaupun tubuh anda sehat tetapi jika pikiran anda terbelenggu oleh ideologi-ideologi dan kebodohan, anda bukan orang bebas. Kondisi pikiran-lah yang menentukan apakah seseorang itu bebas ataukah seseorang itu terpenjara. Periksalah diri anda.
Bagaimana dengan anda kaum agamawan yang suka melecehkannya jika anda menderita seperti Hawking secara fisik?
Saya membayangkan, kalau anda yang menjadi Stephen Hawking, mungkin sekali anda telah lama memutuskan untuk melakukan
euthanasia, yakni memilih mati dengan disengaja sebagai pilihan terbaik ketimbang menanggung penderitaan berat dalam jangka waktu yang panjang.
Pendek kata, bagi saya, Stephen Hawking lebih sehat dari orang sehat, lebih hidup dari orang hidup, dan... lebih tangguh dari pahlawan perang manapun, dan orang tercerdas di planet Bumi untuk saat ini. Karena itu pantaslah jika saya sangat mengaguminya.
Setelah Albert Einstein, orang umumnya memandang Stephen Hawking sebagai orang tercerdas di dunia kita masa kini.
Saat ditanya berapa peringkat IQ-nya, Hawking menjawab,
“Aku tidak tahu. Orang yang membangga-banggakan IQ mereka adalah para pecundang.”/7/
Jika anda sebagai agamawan suka melecehkan Stephen Hawking, cobalah periksa diri anda sendiri, apakah anda bisa menulis buku-buku sains dengan kualitas seperti yang telah ditulis sang mahafisikawan ini:
A Brief History of Time (1998);
The Universe in A Nutshell (2001);
A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes (2009); dan
The Grand Design (bersama Leonard Mlodinow, 2010)?
Tapi pastilah terlalu muluk, bak pungguk merindukan bulan, jika saya meminta anda menulis buku-buku sejenis yang telah ditulis Hawking. OK-lah, sekarang saya hanya menganjurkan anda untuk membaca dan memahami buku-buku sang mahafisikawan ini. Setelah itu, sikap dan pandangan anda terhadapnya
kali-kali saja akan berubah total.
Sekarang, sebagai sebuah ujian untuk anda, coba jawab, apakah anda bisa memahami apa yang dinamakan “radiasi Hawking”, yang ditemukan olehnya tahun 1974?
Jika anda tidak tahu, baiklah saya jelaskan. Menurut Hawking,
black holes dapat memancarkan energi, partikel dan cahaya kendatipun sebuah
black hole itu memiliki forsa gravitasi yang sangat kuat sehingga tak ada sesuatupun yang bisa luput dari sedotannya, bahkan juga cahaya.
Keberadaan
black holes adalah suatu keniscayaan yang diprediksi oleh teori relativitas umum Albert Einstein sebagai sebuah teori tentang gravitasi yang sampai saat ini dipandang sebagai teori gravitasi yang terbaik yang kita miliki.
Dalam sebuah
black hole atau
lubang hitam terdapat massa positif yang terlepas keluar darinya sebagai panas dan memancarkan radiasi dan cahaya. Selain itu, terdapat juga massa negatif yang jatuh ke dalam
black hole sendiri, yang secara bertahap menyusutkan massa keseluruhan sebuah
black hole hingga akhirnya
black hole ini sendiri akan menjadi satu titik (lebih kecil dari atom) sangat massif dan berenergi besar yang akan mendentum― inilah
singularitas.
Jika singularitas ini terus mengecil, tanpa batas, infinite, maka kita memperoleh infinitesimal, sesuatu yang infinitely small, dan jika terus mengecil sampai akhirnya lenyap, menjadi nothing, maka nothing menjadi infinity. Menakjubkan, bukan?
Para saintis baru saja (Oktober 2014) mengonfirmasi temuan yang sejalan dengan teori “radiasi Hawking”. Menurut mereka, partikel-partikel (yang memancarkan frekuensi radio) yang dipancarkan “lubang-lubang hitam” yang sangat massif nyaris dalam kecepatan cahaya dapat mencegah terbentuknya bintang-bintang baru di dalam galaksi-galaksi tua. Gas panas yang bebas oleh partikel-partikel ini dicegah mendingin, alhasil bintang-bintang bayi tidak dilahirkan./8/
Pahamkah anda? Jika tidak, ya akuilah bahwa diri anda terlalu kecil jika dihadapkan kepadanya; jadi, jangan menghakiminya hanya karena dia lumpuh total.
Tapi saya positif terbeban untuk memperluas pengetahuan anda tentang lubang-lubang hitam, “black holes”. Yang ada bukan saja lubang-lubang hitam rata-rata, tetapi juga lubang-lubang hitam “supermasif”. Apa itu?
Lubang hitam supermasif adalah sebuah “pipa” kosmik yang dengan sangat kuat menghisap segala materi dan menjadikannya sebuah titik yang densitasnya tidak terbatas, infinite, yang dibentuk dari massa ratusan ribu hingga milyaran bintang yang terkompresi.
Para astronom kini berpendapat bahwa ada jutaan lubang hitam supermasif dalam jagat raya kita, jauh lebih banyak dari yang diperkirakan semula.
Pendapat ini muncul setelah baru-baru ini ditemukan lima lubang hitam supermasif pada pusat-pusat lima galaksi, yang semula tersembunyi dalam selubung debu dan gas kosmik, oleh tim astronom Inggris yang dipimpin George Lansbury yang bekerja di Centre for Extragalactic Astronomy, Universitas Durham.
Temuan itu didapat dengan menggunakan Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) milik NASA, yang mengorbit sebuah observatorium yang diluncurkan tahun 2012. Teleskop ini dirancang untuk dapat menangkap sinar X yang berenergi sangat besar yang dipancarkan objek-objek yang jauh./9/
Sumbu tebal warna putih tegak lurus pada pusat galaksi, itulah lubang hitam supermasif
Pipa kosmik itu sebetulnya jet atau semburan kuat plasma atau gas-gas yang terionisasi
Di penghujung Januari 2014 Stephen Hawking menyatakan bahwa “lubang hitam tidak ada”, dan akibatnya banyak orang kebingungan karena tidak menempatkan pernyataannya ini dalam konteks seluruh pendapatnya tentang lubang hitam, “Event Horizon” (EH), dan “Paradoks ‘Firewall’ Lubang Hitam”.
EH adalah batas-batas yang tidak kasat mata yang dipikirkan berbentuk sebuah kubah yang menyelubungi setiap lubang hitam. Melampaui batas-batas kubah EH tidak ada sesuatupun, termasuk cahaya dan informasi, yang akan bisa luput dari tarikannya.
Kepada jurnal Nature, Stephen Hawking menyatakan bahwa menurut teori fisika klasik, tidak ada sesuatupun yang bisa lepas dari daya sedot sebuah lubang hitam.
Tapi teori quantum memungkinkan energi dan informasi luput dari tarikan sebuah lubang hitam, berhubung efek-efek quantum di sekitar sebuah lubang hitam menyebabkan ruangwaktu berfluktuasi dengan sangat liar sehingga suatu batas tajam tidak akan terbentuk atau tidak akan ada; atau, dengan kata lain, menurut mekanika quantum EH tidak akan pernah ada.
Sebagai ganti EH, Stephen Hawking mengusulkan sebuah pilihan lain yang dinamakannya “Apparent Horizon” (AH), yakni kubah pembatas yang hanya untuk sementara waktu saja menggenggam materi dan energi sebelum akhirnya melepaskan kembali keduanya meskipun sudah dalam bentuk yang tidak rapih lagi, tetapi kacau.
Pendapat baru Stephen Hawking ini tentang AH dimaksudkannya untuk memecahkan apa yang selama ini dikenal sebagai “Paradoks ‘Firewall’ Lubang Hitam” yang ditemukan oleh fisikawan Joseph Polchinski dari Kavli Institute dan kawan-kawannya berdasarkan teori quantum.
Menurut teori quantum, EH haruslah berubah menjadi suatu kawasan yang berenergi sangat besar, yang akan membakar sampai habis apapun yang masuk ke dalam batas-batas EH. Kawasan yang berenergi sangat besar ini dinamakan kawasan “Firewall” (“Dinding Api”?).
Di mana paradoksnya? Berdasarkan relativitas umum Einstein, para fisikawan telah lama beranggapan bahwa jika seorang astronot dengan sial terjatuh ke dalam sebuah lubang hitam, sang astronot ini akan dengan riang melewati EH (dengan sama sekali tidak menyadari nasib akhirnya!) sebelum akhirnya perlahan-lahan disedot ke dalam lubang hitam yang berakhir pada singularitas (inti sangat padat tanpa batas dari sebuah lubang hitam).
Paradoksnya adalah hukum-hukum dalam mekanika quantum (yang mengendalikan partikel-partikel yang berukuran subatomik) yang mengharuskan terbentuknya Firewall tidak memungkinkan sang astronot itu bisa dengan gembira melewati kubah EH yang juga menjadi Firewall; alhasil, begitu masuk ke EH, sang astronot langsung dibakar sampai kering bak sepotong ayam goreng krispi KFC.
Usul baru Stephen Hawking tentang AH, yang mengharuskan EH dianulir, membuat Paradoks Firewall tidak ada lagi.
Kata Stephen Hawking, batas-batas yang real bukanlah EH, tetapi AH; alhasil, karena EH tidak ada, maka lubang hitam juga tidak ada, dalam arti: tidak ada sistem yang darinya cahaya tidak dapat lepas selamanya./10/
Tapi Joseph Polchinski yang sudah dirujuk di atas bersikap skeptis terhadap gagasan baru AH Stephen Hawking, bahwa suatu lubang hitam dapat ada dalam alam kendatipun tidak memiliki EH.
Menurut Polchinski, fluktuasi ruangwaktu yang berlangsung keras, yang diperlukan untuk meniadakan EH sangat jarang terjadi dalam jagat raya. Secara teoretis, penggabungan gravitasi dan mekanika quantum dapat menyingkirkan EH, tetapi dalam kenyataannya efek-efek mekanika quantum yang dibayangkan Stephen Hawking terhadap ruangwaktu jarang terjadi.
Kembali ke pribadi Stephen Hawking. Fisiknya memang lumpuh, tapi ternyata dia juga memiliki jiwa yang relung-relungnya dalam, yang tersentuh oleh kebesaran jagat raya dan keajaiban semua yang ada. Kata sang mahafisikawan ini kepada anda,
“Ingatlah untuk menatap ke atas, ke bintang-bintang, dan jangan menatap ke bawah ke kaki anda. Cobalah pahami apa yang anda lihat, dan tetaplah terpesona seperti kanak-kanak saat anda bertanya-tanya apa yang telah membuat jagat raya ini ada.”
Sedalam itukah jiwa anda yang suka merendahkannya?
Hawking juga respek pada kaum perempuan. Meskipun pernah bercerai, Hawking dapat mengakui bahwa kaum perempuan memiliki kedalaman jiwa yang tidak terukur ketika dia menyatakan bahwa misteri terbesar dalam jagat raya ini bukan misteri fenomena fisika, tetapi misteri kaum perempuan.
Selain itu, perhatian Hawking terhadap ketahanan kehidupan manusia dan peradaban yang mereka telah bangun juga besar.
Saat ditanya, kelemahan apa yang ada pada manusia yang akan bisa membahayakan dunia di masa depan, dia menjawab bahwa sifat agresif manusia itulah yang paling berbahaya, sebab agresi akan bisa memicu perang nuklir dalam waktu dekat. Katanya,
“Kita perlu mengganti agresi dengan empati yang akan membawa kita bersama ke suatu keadaan damai yang memberi kebahagiaan dan cinta.”
Katanya lagi,
“Agresi pada masa kehidupan manusia goa dapat bermanfaat untuk mendatangkan ketahanan hidup, untuk mendapatkan lebih banyak makanan, wilayah kekuasaan atau seorang teman hidup untuk mendatangkan keturunan; tapi kini agresi adalah ancaman yang akan membinasakan kita semua.”/11/
Dus, jika Stephen Hawking sebagai sang fisikawan jenius terbesar abad ke-21 memiliki hati yang sangat lembut dan perhatian besar pada masa depan umat manusia, bahkan pada kaum perempuan, anda benci, saya tidak bisa memahami anda.
Jika anda membencinya karena dia ateis, anda salah besar. Bersama Peter Higgs yang menerima Hadiah Nobel untuk teorinya tentang partikel Higgs boson yang sudah terbukti benar, Stephen Hawking adalah seorang ateis yang tidak agresif, tetapi berhati lembut dan mampu bersahabat dengan semua orang.
Jangan anda bandingkan ateis Peter Higgs dan ateis Stephen Hawking dengan ateis Richard Dawkins yang agresif dan suka menyerang agama-agama dan Tuhan meskipun Dawkins tidak percaya Tuhan itu ada!
Walaupun ketiganya ateis, Higgs dan Hawking adalah ateis yang kalem dan tenang, tidak agresif dan tidak meledak-ledak gaya Dawkins sebagai seorang ateis fundamentalis. Richard Dawkins dkk dikenal sebagai para pendiri dan pembela agresif New Atheism yang sudah saya bongkar habis dalam sebuah tulisan panjang akademik saya./12/
Di lain pihak, kaum agamawan suka memanfaatkan Albert Einstein (1879-1955) yang diperlawankan dengan Stephen Hawking oleh mereka.
Kita tahu, Einstein dikenal agung terutama selain lewat persamaannya yang hebat E=mc2, juga lewat dua teori relativitasnya: relativitas umum dan relativitas khusus.
Teori relativitas umum menyatakan bahwa ruangwaktu (spacetime) dibuat terceruk atau terlipat (warped) oleh objek-objek yang massif dan berenergi besar, dan bahwa forsa gravitasi adalah hasil dari pencerukan ruangwaktu ini.
Suatu benda massif seperti sebuah planet (yang memiliki massa dan energi) mendistorsi ruangwaktu, alhasil benda-benda yang terletak berdekatan ditarik oleh cerukan atau cekungan yang ditimbulkan oleh distorsi ini― tarikan inilah forsa gravitasi.
Mudahnya begini: jika ada sebuah lubang cekung yang dalam di permukaan tanah, maka air hujan yang turun deras di berbagai tempat ditarik dan mengalir masuk ke dalam cekungan itu. Tarikan inilah, menurut teori Einstein, forsa gravitasi.
Forsa gravitasi ini tidak bergerak linier, tapi bergelombang, ibarat riak gelombang air di danau yang bergerak konsentrik dari titik jatuhnya sebuah batu yang kita lemparkan ke tengah danau. Inilah gravitational waves.
Cermati gambar di atas. Sebuah benda massif seperti sebuah planet membuat dimensi ruangwaktu terceruk, membuat cekungan; alhasil benda-benda lain yang dekat dengan planet itu ditarik masuk ke dalam kawasan atau medan cekung itu; tarikan inilah forsa gravitasi. Karena enerji itu ekuivalen dengan massa, forsa gravitasi memiliki massa (sekalipun sangat ringan) dalam wujud partikel graviton.
Teori relativitas khusus menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya.
Dalam teori relativitas khusus, pengukuran waktu dipandang bergantung pada si pengamat yang melakukan pengukuran itu; dengan demikian, waktu tidak bisa mutlak, sebagaimana dipikirkan Newton sebelumnya, atau dengan kata lain, tidaklah mungkin untuk memberikan kepada setiap peristiwa waktu yang setiap pengamat akan setujui.
Ruang dan waktu saling merangkul, tidak terpisah, membentuk dimensi ruangwaktu atau
spacetime dimension. Ditambah dengan cahaya sebagai sebuah dimensi, kita hidup dalam kungkungan lima dimensi ini.
Dengan berdasar pada teori Einstein, Stephen Hawking menyatakan sesuatu yang menarik; katanya,
“Perjalanan lintas-waktu biasanya dipandang sebagai fiksi sains belaka. Tapi teori relativitas umum Einstein memungkinkan kita mencerukkan ruangwaktu sehingga anda dapat lepas landas dalam sebuah roket dan kembali lagi sebelum anda berangkat.”/13/
Untuk kepentingan mereka, kaum agamawan suka sekali mengutip sebuah pernyataan Albert Einstein bahwa “sains tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa sains buta”.
Sehabis mengutipnya, mereka langsung berkata, “Lihatlah Einstein itu saintis yang saleh beragama, maka itu hidupnya lurus, sehat dan bugar, tak seperti Stephen Hawking yang lumpuh.” Malah ada agamawan yang sangat eksentrik sampai bisa menyatakan bahwa Einstein adalah seorang Muslim syiah yang hidupnya diberkati Allah.
Pada sisi lain, banyak juga orang Kristen evangelikal menyatakan bahwa Einstein adalah seorang Kristen saleh yang hidupnya diperkenan dan diberkati Yesus.
Kaum agamawan Buddhis juga mengklaim bahwa Einstein pernah menyatakan Buddhisme non-theis adalah agama yang sejalan dengan sains modern.
Harus diakui bahwa Einstein melihat kemungkinan Buddhisme adalah agama yang paling akomodatif terhadap sains modern setelah sang saintis hebat ini membaca tentang Buddhisme lewat tulisan-tulisan Schopenhauer.
Tulis Einstein,
“Jika ada agama yang dapat berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan saintifik modern, agama ini adalah Buddhisme.”
Juga,
“Buddhisme, sebagaimana kami telah pelajari dari tulisan-tulisan hebat Schopenhauer, berisi jauh lebih kuat elemen-elemen perasaan keagamaan kosmik.”/14/
Rupanya kaum agamawan berkepentingan untuk menarik Einstein ke kubu agama mereka masing-masing lalu membaptisnya dan memanfaatkannya.
Pertanyaan pentingnya adalah apakah Einstein seorang saintis yang beragama.
Kalau kita telusuri tulisan-tulisan Einstein tentang Allah dan agama, kita harus simpulkan bahwa Einstein
tidak percaya pada Allah yang diberitakan agama-agama monoteistik, termasuk Allah bangsa Yahudi, bangsanya sendiri. Dia bukan seorang monoteis.
Kalau Einstein memunculkan kata “Allah” dalam tulisan-tulisannya, kata ini diberi makna metaforis olehnya, bukan makna ontologis. Umumnya memang begitu: Kalau seorang saintis memakai kata Allah, kata ini bermakna metaforis, tidak bermakna literal.
Kalau Einstein berkata-kata tentang Allah, bagi dia Allah adalah struktur kosmologis yang sangat mempesonanya, yang ditata oleh hukum-hukum kosmologis.
Bagi sang saintis agung ini, Allah adalah kemahabesaran jagat raya, yang terungkap dalam strukturnya yang sangat menakjubkan, yang dibangun dan ditata dengan berfondasi hukum-hukum kosmik, dan yang bekerja juga lewat hukum-hukum alam ini.
Hanya sebagian kecil saja dari kemahabesaran kosmik ini yang kita sudah dapat pahami lewat sains modern.
Einstein, meski berdarah Yahudi, dengan tegas menolak untuk percaya pada suatu Allah personal yang diberitakan tiga agama monoteistik, Yahudi, Kristen dan Islam.
Pada 22 Maret 1954 Einstein menerima sebuah surat dari Joseph Dispentiere, seorang imigran asal Italia yang telah bekerja sebagai seorang masinis eksperimental di New Jersey. Sang masinis ini telah menyatakan dirinya ateis dan sangat kecewa ketika membaca sebuah berita yang menggambarkan Einstein sebagai seorang yang beragama konvensional. Pada 24 Maret 1954, Einstein menjawab, tulisnya:
“Tentu saja suatu dusta jika anda membaca tentang keyakinan-keyakinan keagamaan saya, suatu kebohongan yang dengan sistimatis diulang-ulang. Saya tidak percaya pada suatu Allah personal dan saya tidak pernah menyangkali hal ini tetapi telah mengungkapkannya dengan jelas. Jika ada sesuatu dalam diri saya yang dapat disebut religius, maka ini adalah suatu kekaguman tanpa batas terhadap struktur dunia yang sejauh ini sains dapat menyibaknya.”/15/
“Saya tidak pernah mengenakan pada Alam suatu maksud dan tujuan, atau apapun yang dapat dipahami sebagai antropomorfisme. Apa yang saya lihat dalam Alam adalah suatu struktur yang menakjubkan, yang dapat kita pahami hanya dengan sangat tidak sempurna, dan hal itu harus mengisi seorang pemikir dengan suatu perasaan kerendahan hati. Ini adalah suatu perasaan religius murni yang tidak ada hubungannya dengan mistisisme.”/16/
Apa yang dimaksud dengan “religius” oleh Einstein, sangat tidak terduga dalam pikiran kaum agamawan,
karena sang saintis ini menyatukan religiositas dengan nalar dan pengetahuan rasional. Einstein menulis,
“Melalui hikmat dan pemahaman, manusia mendapatkan pembebasan yang berjangkauan luas dari segala belenggu pengharapan dan hasrat pribadi, dan dengan itu mereka memperoleh sikap dan perilaku pikiran yang penuh kerendahan hati terhadap keakbaran Nalar yang mewujud dalam kehidupan, dan yang, sedalam-dalamnya, dapat dimasuki manusia.
Sikap dan perilaku akal budi yang rendah hati inilah yang tampak bagiku religius, dalam arti setinggi-tingginya kata ini…. Semakin jauh perkembangan evolusi spiritual manusia, semakin pasti bagiku bahwa jalan menuju religiositas yang murni tidak terletak pada ketakutan akan kehidupan atau ketakutan akan kematian dan iman yang membuta, melainkan pada usaha keras untuk mendapatkan pengetahuan rasional.”
Apa yang menjadi sikap religiusnya, yang terikat erat dengan nalar dan keindahan, dengan ringkas ditulisnya dalam suatu bagian bukunya yang terbit 1949,
The World As I See It, demikian:
“Suatu pengetahuan tentang keberadaan sesuatu yang kita tidak dapat tembus, tentang wujud-wujud nalar terdalam dan keindahan yang paling bercahaya, yang hanya dapat dimasuki oleh nalar kita dalam bentuk-bentuknya yang paling elementer―pengetahuan dan emosi inilah yang membentuk sikap religius sejati; dalam arti inilah, dan hanya dalam arti inilah, aku seorang religius yang sedalam-dalamnya.”/17/
Kalau Einstein menyatakan bahwa “Allah tidak sedang bermain dadu”, Allah dalam pernyataannya ini adalah hukum-hukum sains yang deterministik, hukum-hukum sebab-akibat,
causal laws, dalam jagat raya./18/
Ucapannya itu dilatarbelakangi oleh penolakan dan ketidaksepakatannya terhadap fisika dunia mikroskopik partikel yang dikenal sebagai
mekanika quantum. Dalam fisika quantum, kalau kita mengacu misalnya ke
Prinsip Ketidakpastian Heisenberg yang dibangun berdasarkan observasi atas perilaku partikel, tampaknya determinisme saintifik dirobohkan padahal Einstein memegangnya dengan kuat.
Ada suatu perasaan mistikal muncul di saat foto ini kupandang dalam-dalam: dua pemikir besar sedang ngobrol...!
Tentang determinisme saintifik dan perasaan religius yang istimewa yang timbul dari pencarian ilmu pengetahuan, dalam jawabannya (24 Januari 1936) terhadap pertanyaan seorang anak perempuan yang bernama Phyllis (kelas enam sekolah Minggu Gereja Riverside, Amerika) apakah Einstein sebagai seorang saintis berdoa (19 Januari 1936), Einstein menulis demikian:
“Para saintis percaya bahwa setiap peristiwa, termasuk berbagai urusan manusia, terjadi karena hukum-hukum alam. Karena itu, seorang saintis tidak dapat cenderung percaya bahwa jalannya peristiwa-peristiwa dapat dipengaruhi oleh doa, yakni oleh suatu permintaan yang ditujukan ke suatu Oknum Supernatural.
Tapi kita harus akui bahwa pengetahuan kita yang sebenarnya mengenai daya-daya kekuatan alam ini tidak sempurna, sehingga pada akhirnya kepercayaan pada keberadaan suatu roh fundamental yang paling menentukan berpijak pada semacam iman. Kepercayaan ini dipegang banyak orang di mana-mana, bahkan ketika ilmu pengetahuan sudah maju seperti sekarang ini.
Tetapi juga, setiap orang yang terlibat dengan serius dalam usaha-usaha mencari ilmu pengetahuan menjadi yakin bahwa suatu roh menyatakan diri di dalam hukum-hukum alam semesta. Roh ini jauh lebih tinggi dibandingkan roh manusia. Dengan demikian, pengejaran ilmu pengetahuan juga membawa orang ke suatu perasaan religius yang istimewa, yang tentu saja sangat berbeda dari religiositas seseorang yang kurang pengetahuan.”/19/
Lebih lanjut tentang determinisme saintifik, Einstein menulis,
“Aku tidak dapat membayangkan suatu Allah personal yang langsung mempengaruhi tindakan-tindakan orang per orangan, atau secara langsung duduk mengadili semua ciptaan yang telah dibuatnya sendiri. Aku tidak dapat membayangkan semua ini kendatipun kausalitas mekanistik [/deterministik] dalam batas tertentu telah diragukan oleh sains modern [Dalam hal ini, yang Einstein maksudkan adalah mekanika quantum yang dipandang menolak determinisme saintifik].
Religiositasku memberi tempat utama pada kekaguman dan kerendahan hati terhadap roh yang mahaagung tanpa batas, yang menyatakan dirinya sendiri di dalam sedikit hal mengenai realitas yang kita dapat pahami dengan akal kita yang lemah dan fana. Yang terpenting adalah moralitas, untuk kita tentunya dan bukan untuk Allah.”/20/
Dalam surat-suratnya kepada fisikawan quantum Max Born, Albert Einstein mengungkapkan kepercayaannya yang kokoh pada hubungan-hubungan kausal sebab-akibat dalam suatu dunia objektif. Tulisnya, antara lain:
“Anda percaya pada suatu Allah yang bermain dadu [dengan alam ini], sedangkan aku percaya pada hukum kausal dan orde yang lengkap dan teratur dalam suatu dunia yang secara objektif ada, dunia yang aku coba tangkap dan pahami sekalipun dengan cara yang sangat spekulatif. Aku dengan kokoh percaya ini, tetapi aku sungguh berharap bahwa seseorang nanti akan menemukannya dengan cara yang lebih realistik, atau dengan landasan yang lebih real ketimbang yang dengan untung-untungan telah kutemukan.
Bahkan sukses awal yang besar dari teori quantum tidak membuatku percaya pada permainan dadu yang mendasar, meskipun aku sadar betul bahwa beberapa rekan sejawat kita yang lebih muda menafsirkan posisiku ini sebagai konsekwensi dari usiaku yang sudah uzur.”/21/
Begitu juga, kalau Einstein menyatakan “sains tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa sains buta” (Albert Einstein, 1941), dia tidak sedang membela agama-agama monoteistik atau menyamakan sains dan agama atau sebaliknya.
Ucapannya itu terikat erat dengan pendapatnya bahwa spiritualitas atau religiositas tertinggi diraih lewat nalar dan ilmu pengetahuan rasional. Juga penting diingat terus bahwa kalau Einstein menulis tentang Allah, baginya Allah adalah ungkapan metaforis dari daya pesona yang muncul dari struktur kosmologis yang taat pada hukum-hukum sains, sejauh hukum-hukum ini sudah dapat dipahami.
Hemat saya, posisi Einstein ini memiliki suatu landasan teologis yang kuat. Begini: Jika anda percaya pada Tuhan Yang Mahatahu, dus Tuhan adalah sumber kemahatahuan, maka ilmu pengetahuan yang dibangun lewat penalaran logis dan rasional, adalah jalan agung tanpa ujung menuju Tuhan Yang Mahatahu. Religiositas semacam ini tinggi, tidak terpenjara dalam dikotomi klasik agama versus ilmu pengetahuan dan akal budi.
Dalam religiositas ini, keingintahuan atau kuriositas sebagai salah satu pendorong lahirnya ilmu pengetahuan modern diberi tempat luas untuk bergerak tanpa dihalangi. Tuhan dalam metafora Taman Eden yang melarang keras Hawa mengikuti keingintahuannya tentang khasiat buah Pohon Pengetahuan (moral), yang mendorongnya ingin mencicipi buah itu, bukanlah Tuhan yang dipikirkan Einstein.
Kepada Eric Gutkind yang pada 1954 telah mengirimkannya sebuah buku yang berjudul Choose Life: The Biblical Call to Revolt, tentang Allah bahkan Einstein menulis,
“Kata Allah bagiku tidak lebih dari sekadar ungkapan dan produk kelemahan-kelemahan manusia, dan Alkitab tidak lebih dari sekadar sebuah kumpulan legenda yang mulia tetapi masih primitif. Tidak ada penafsiran, betapapun tajam, yang dapat mengubah hal ini.”/22/
Dalam banyak segi, Allah dalam pandangan Einstein sejalan dengan Allah dalam pandangan Baruch de Spinoza (1632-1677), Allah sebagai hukum-hukum sains yang menata jagat raya ini dalam suatu harmoni yang menakjubkan. Tulis Einstein,
“Aku percaya pada Allah Spinoza yang mewahyukan diri dalam harmoni dan keteraturan segala yang ada, bukan pada Allah yang sibuk mengurusi nasib dan tindakan manusia.”/23/
Lagi dia menulis:
“Tampak olehku bahwa ide tentang suatu Allah personal adalah suatu konsep antropologis yang aku tidak dapat ambil dengan serius. Aku juga merasa bahwa aku tidak dapat membayangkan adanya suatu kehendak atau suatu tujuan di luar kawasan kehidupan manusia.
Pandangan-pandanganku dekat dengan pandangan-pandangan Spinoza: kekaguman pada keindahan, dan kepercayaan terhadap, simplisitas logis dari orde semesta yang kita dapat pahami dengan rendah hati dan hanya dengan tidak sempurna.
Aku percaya bahwa kita harus memuaskan diri kita dengan pengetahuan dan pemahaman yang tidak sempurna dan memperlakukan nilai-nilai dan kewajiban-kewajiban moral sebagai sebuah masalah yang murni manusiawi― masalah terpenting dari semua masalah manusia.”/24/
Dus, dalam dunia sains, ada dua metafora tentang Allah, yakni Allah Baruch de Spinoza dan Allah Einstein, yakni hukum-hukum kosmologis yang menata dan membangun jagat raya dengan sangat menakjubkan dan deterministik dan belum terpahami semuanya.
Kalaupun Einstein mempunyai visi tentang suatu agama masa depan, agama ini dirumuskannya demikian:
“Agama masa depan akan berupa suatu agama kosmik. Agama ini harus melampaui Allah personal dan menghindari dogma dan teologi.
Mencakup baik yang natural maupun yang spiritual, agama ini harus didasarkan pada suatu perasaan keagamaan yang muncul dari pengalaman bahwa segala sesuatu yang alamiah dan yang spiritual ada dalam suatu kesatuan yang bermakna.
Buddhisme menjawab gambaran tentang agama yang demikian. Jika ada agama apapun yang dapat berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan saintifik modern, agama ini adalah Buddhisme.”
“Agama kosmik” ini menjadi suatu sistem kepercayaan (belief system) yang dipegang Einstein.
Dia mendefinisikan sistem kepercayaannya ini sebagai suatu “orde yang ajaib, yang mempesona, yang menyatakan dirinya di dalam keseluruhan alam dan juga di dalam dunia ide-ide” yang tidak berisi suatu Allah personal yang memberi pahala atau yang menghukum berdasarkan kelakuan setiap manusia./25/
Bagi Einstein jelaslah bahwa agamanya, atau sistem kepercayaannya, bukan teisme, tetapi suatu sistem kepercayaan yang tidak terpisah dari alam, nalar, pengetahuan rasional, ide-ide, dus dari alam dan ilmu pengetahuan. Inilah agama Einstein, agama kosmik.
Dalam agama kosmiknya ini, dia mempersatukan agama dan ilmu pengetahuan, tidak mempertentangkan keduanya. Dari sudut pandang ini sajalah Einstein dengan tegas dapat menyatakan bahwa “sains tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa sains buta.”/26/
Dalam sistem kepercayaannya ini, kalau nama “Allah” dipakai, maka, tulis Einstein,
“Allah adalah suatu misteri, tetapi misteri yang dapat dipahami. Aku hanya bisa terpesona saat aku mengobservasi hukum-hukum alam. Tentu tidak akan ada hukum-hukum jika tidak ada pemberinya. Tapi siapa sang pemberi hukum-hukum alam ini? Tentu saja bukan seperti seorang manusia yang diagungkan.”/27/
Dengan menyatakan ini, jelaslah bahwa Einstein menolak antropomorfisme teologis dalam teisme (Yahudi, Kristen dan Islam) yang menggambarkan dan membahasakan suatu sosok adikodrati yang dinamakan Allah dalam wujud-wujud dan sifat-sifat seperti manusia.
Jadi, siapa pemberi hukum-hukum alam itu? Sesuatu yang impersonal dan alamiah. Einstein membahasakannya sebagai “sang keindahan, sang keagungan, sang orde yang mempesona, yang menyatakan diri di dalam alam”, yang dialami sebagai “jagat raya dalam satu kesatuan yang signifikan dan menyeluruh.”/28/
Sekalipun Einstein berbicara tentang hal-hal yang spiritual, sang saintis ini tidak percaya bahwa manusia memiliki roh yang akan meninggalkan tubuh ketika manusia mati, salah satu kepercayaan kuat dalam teisme. Tulisnya,
“Aku tidak dapat membayangkan suatu Allah yang memberi pahala dan yang menghukum objek-objek ciptaannya, yang memiliki tujuan-tujuan yang disusun berdasarkan model dari kita sendiri, suatu Allah, pendek kata, yang hanya merupakan suatu cerminan kelemahan moral manusia. Aku juga tidak dapat percaya bahwa kita orang per orangan akan bertahan kekal, meninggalkan tubuh kita, setelah kematian, kendatipun jiwa-jiwa yang ringkih memegang pikiran-pikiran semacam itu karena rasa takut atau karena egotisme yang memalukan.”/29/
Lagi, tulis Einstein,
“Aku tak dapat membayangkan suatu Allah yang memberi pahala dan menghukum ciptaan-ciptaannya, atau yang memiliki kehendak semacam itu yang kita sendiri sadari dalam diri kita sendiri.
Juga aku tidak dapat membayangkan atau, sebaliknya, menginginkan bahwa seorang manusia akan bertahan setelah kematian tubuh jasmaniahnya; biarlah jiwa-jiwa yang ringkih, karena rasa takut atau karena egotisme yang tak masuk akal, berharap pada pemikiran semacam itu.
Aku puas dengan misteri keabadian kehidupan, bersama dengan kesadaran dan penglihatan sekilas atas struktur yang menakjubkan dari dunia yang sekarang ada, bersama dengan usaha yang serius untuk memahami Nalar sebagian saja, sekalipun sangat sedikit, yang menyatakan dirinya sendiri dalam alam.”/30/
Lagi,
“Aku tidak percaya pada keabadian seorang manusia individual, dan aku memandang etika sepenuhnya adalah perkara manusia tanpa ditopang oleh suatu otoritas adiinsani di baliknya.”/31/
Jelaslah, etika atau moralitas yang diperlukan manusia untuk mengatur masyarakat, bagi Einstein, bukanlah moralitas yang bersumber pada agama, melainkan, tulisnya,
“Perilaku moral manusia harus dilandaskan secara efektif pada simpati, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan serta ikatan-ikatan sosial; untuk moralitas, basis keagamaan tidak diperlukan. Sesungguhnya betapa malangnya manusia jika tindakan-tindakan moralnya dikendalikan oleh ketakutan akan penghukuman dan pengharapan akan mendapatkan pahala setelah kematian.”/32/
Dan lagi,
“Tidak ada yang ilahi pada moralitas; melainkan moralitas itu sepenuhnya adalah urusan manusia.”
Penolakan Einstein atas peran Allah dalam perilaku moral manusia, yang akan menentukan apakah seseorang akan dibenarkan atau dipersalahkan oleh-Nya, tentu saja tidak terhindar mengingat dia memegang kepercayaan penuh pada determinisme saintifik.
Dalam determinisme ini, semua kelakuan manusia dan bagaimana mereka akan bertanggungjawab atas semua kelakuan mereka tidak ditentukan oleh suatu kuasa eksternal di dunia supernatural, tetapi oleh hukum-hukum sebab-akibat, hukum-hukum kausal, yang merupakan hukum-hukum alam yang baginya berlaku abadi dan tidak pandang bulu.
Namun hal itu tidak berarti tidak ada tanggungjawab manusia untuk menghasilkan moralitas. Bagi Einstein, salah satu tugas terpenting dari pendidikan adalah menjadikan kita semua bermoral dalam semua tindakan kita. Tulisnya,
“Usaha terpenting yang manusia harus lakukan adalah berjuang keras untuk menghasilkan moralitas dalam semua tindakan kita. Keseimbangan batin kita bahkan kehidupan kita sendiri bergantung pada moralitas. Hanya jika semua tindakan kita bermoral, keindahan dan martabat akan muncul dalam kehidupan. Menjadikan ini sebagai suatu daya kehidupan dan membuat kita menyadarinya dengan jelas mungkin adalah tugas terpenting dari pendidikan.
Fondasi moralitas haruslah tidak dibuat bergantung pada mitos atau diikatkan pada otoritas apapun supaya keraguan atas mitos itu atau keraguan akan legitimasi otoritas itu tidak membahayakan fondasi yang berupa pertimbangan dan tindakan yang matang.”/33/
Jadi, hai kaum agamawan, janganlah kalian, ringkas kata, mengagamakan Einstein atau berusaha menariknya ke kubu kalian. Let Einstein be Einstein.
Sangat jelas, Einstein menolak monoteisme Yahudi, agama moyangnya. Suatu Allah personal baginya adalah sebuah konsep teologis yang tidak bermakna, bahkan tidak masuk akalnya.
Tetapi, pada sisi lain, saya juga mencatat ada banyak orang ateis yang selalu memanfaatkan dan kerap mengutip Einstein untuk mendukung keyakinan-keyakinan ideologis ateisme mereka.
Bisa jadi, orang yang telah membaca apa yang saya sudah kemukakan di atas akan menyimpulkan dengan keliru bahwa sang saintis akbar ini adalah seorang ateis.
Celakanya, mereka juga salah memahami Einstein. Karena itu, saya juga mau memperingatkan: Hai kaum ateis, janganlah tarik Einstein ke kubu kalian untuk membenarkan ideologi ateisme kalian. Let Einstein be Einstein!
Jika Einstein bukan seorang teis, dan juga bukan seorang ateis, lantas apa keyakinannya tentang Tuhan?
Dengan sangat jelas Einstein menyatakan posisinya sebagai seorang agnostik, seorang yang tidak dapat dengan yakin menyatakan Allah ada dan juga tidak dapat dengan yakin menyatakan Allah tidak ada.
Pendek kata, seorang agnostik adalah seorang yang mengaku tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah Allah ada atau apakah Allah tidak ada. Seorang agnostik hanya akan menjawab, saya tidak tahu (Yunani: a-gnosis) apakah Allah ada ataukah Allah tidak ada.
Sebagai respons atas pertanyaan apakah Einstein percaya atau tidak percaya pada Allah, dalam sebuah wawancara yang diterbitkan 1930 dalam buku G. S. Viereck, Glimpses of the Great, Einstein menyatakan hal berikut ini.
“Pertanyaan anda [tentang Allah] adalah pertanyaan yang paling sulit dalam dunia ini. Ini bukanlah sebuah pertanyaan yang saya dapat jawab dengan ya atau tidak. Saya bukan seorang ateis.
Saya juga tidak tahu apakah saya dapat mendefinisikan diri saya sebagai seorang panteis. Masalah yang terkandung dalam pertanyaan ini terlalu luas untuk pikiran-pikiran kita yang terbatas. Bolehkah saya menjawabnya dengan sebuah perumpamaan?
Pikiran manusia itu, betapapun tingginya telah dilatih, tidak dapat memahami jagat raya. Kita berada dalam posisi sebagai seorang anak kecil yang memasuki sebuah perpustakaan besar yang dinding-dindingnya tertutup sampai ke langit-langit oleh buku-buku yang ditulis dalam banyak bahasa yang berbeda.
Sang anak ini tahu bahwa seseorang pastilah telah menulis semua buku itu. Tetapi dia tidak tahu siapa para penulis semua buku itu dan bagaimana cara menulis isi buku-buku itu. Si anak tidak memahami bahasa-bahasa yang dipakai dalam buku-buku itu.
Tetapi si anak menemukan buku-buku itu disusun lewat sebuah perencanaan tertentu, ditata dengan cara yang misterius, yang tidak dapat dipahaminya, tetapi hanya dapat diduga-duganya dengan samar-samar.
Itulah, menurut saya, suatu sikap pikiran manusia, bahkan pikiran manusia yang terbesar dan paling beradab, terhadap Allah.
Kita melihat suatu jagat raya yang tersusun dengan menakjubkan, yang patuh pada hukum-hukum tertentu, tapi kita memahami hukum-hukum itu hanya samar-samar. Pikiran kita yang terbatas tidak dapat memahami forsa misterius yang menggerakkan rasi-rasi bintang-bintang.
Saya terpesona pada panteisme Spinoza. Saya bahkan lebih kagum lagi pada sumbangan-sumbangannya bagi pemikiran modern. Spinoza adalah filsuf modern terbesar, sebab dialah filsuf pertama yang memikirkan tubuh dan jiwa sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua hal yang terpisah.”/34/
Bahwa Einstein itu agnostik dan menolak baik posisi ateis maupun posisi teis, dengan sangat tajam dinyatakan olehnya, demikian:
“Berulangkali aku telah katakan bahwa dalam pendapatku ide tentang suatu Allah personal adalah ide yang kekanak-kanakan.
Anda dapat menyebut saya agnostik, tapi saya tidak ikut menghayati semangat tempur dan fanatisme dari orang-orang yang mengaku ateis.
Semangat dan fanatisme mereka itu timbul dari keinginan membara dan kepedihan hati untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu indoktrinasi keagamaan yang mereka telah terima sewaktu masih remaja.
Saya memilih untuk bersikap rendah hati sejalan dengan kelemahan pemahaman intelektual kita terhadap alam dan hakikat kehidupan kita sendiri.”/35/
“Meskipun terdapat harmoni dalam jagat raya, yang dengan pikiran insaniku yang terbatas dapat kupahami, masih saja ada orang yang berkata bahwa Allah itu tidak ada.
Tapi hal yang sungguh-sungguh membuatku marah adalah bahwa mereka mengutip aku untuk menunjang pandangan-pandangan mereka yang seperti itu.”/36/
Dengan sangat keras, Einstein menulis tentang orang-orang ateis, demikian:
“Orang-orang ateis yang fanatik itu... bak budak-budak yang masih merasa beratnya rantai-rantai yang pernah membelenggu mereka, yang sebetulnya mereka telah lepaskan dan buang setelah berjuang sangat keras. Dalam sakit hati mereka terhadap ‘candu masyarakat’, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak dapat tahan mendengar berbagai musik yang disenandungkan dunia-dunia.”/37/
Kendatipun Einstein tidak mempercayai suatu Allah personal dalam teisme, dia menyatakan bahwa dia tidak akan pernah berusaha untuk menyerang kepercayaan ini karena
“aku lebih menyukai kepercayaan teistik ini ketimbang orang melepaskan sama sekali pandangan-pandangan yang transendental.”/38/
Itulah Albert Einstein, seorang yang dengan jelas menyatakan diri agnostik.
Selanjutnya jangan lagi anda membenturkan Albert Einstein dengan Stephen Hawking.
Para saintis sejati tidak akan berkelahi satu sama lain, sebab semua cabang sains bisa berkembang dan bertambah maju karena semuanya dibangun secara kolektif, akumulatif dan dialektis, hasil kerjasama berbagai saintis di banyak lokasi geografis dan di sepanjang sejarah perkembangan sains, sejak dulu hingga terus ke masa depan tanpa batas.
Akhirnya, pesan saya adalah, kalau anda mau menunjukkan bahwa agama anda sejalan dengan sains modern, caranya bukan dengan merangkul atau membajak saintis-saintis besar seperti Einstein ke dalam kubu agama anda, sebab sains itu tidak berafiliasi dengan agama apapun.
Apapun agama seseorang, jika orang ini memakai metode-metode dan penalaran-penalaran saintifik yang sama dalam menyelidiki suatu fenomena empiris, hasil-hasilnya akan selalu sama di manapun dan kapanpun. Jika temuan-temuan ilmiahnya sudah teruji kebenarannya, sudah terverifikasi, maka temuan-temuan yang sama akan juga diperoleh meski metode-metode riset yang digunakan berbeda.
Seseorang menjadi ilmuwan bukan karena ada teori-teori ilmiah modern di dalam kitab suci agamanya yang ditulis di era prailmiah dan pramodern, yang tinggal dia comot dari sana sini dalam kitab sucinya, lalu dia menerima Anugerah Nobel sains. Tetapi karena dia memiliki kecakapan dan kecerdasan untuk membangun metode-metode pengkajian ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan atau memecahkan hal-hal dalam dunia empiris yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan.
Tidak akan pernah terjadi seseorang tiba-tiba menjadi seorang saintis besar hanya karena dia hafal seluruh ayat kitab sucinya.
Selain itu, temuan-temuan seorang saintis juga harus bisa diuji kebenarannya oleh para saintis lain yang sezaman atau lintaszaman di bagian-bagian dunia yang berbeda.
Ilmu pengetahuan itu universal. Tidak ada ilmu pengetahuan yang esoteris, hanya berlaku dan benar bagi lingkungan sendiri yang terbatas dan rahasia. Cinta rahasia ada. Ilmu pengetahuan rahasia tidak ada.
Jika ada seseorang yang mengklaim telah sukses membangun sebuah ilmu pengetahuan rahasia dan teknologi yang juga rahasia, temuannya ini bukan iptek tetapi ngelmu klenik yang esoteris atau, seperti sudah banyak terbukti, suatu penipuan. Di Barat dan di Timur orang semacam ini banyak dan selalu lahir, datang dan pergi, pergi dan datang.
Ke depan ini, hal yang seharusnya anda lakukan adalah: pelajari sains dengan mendalam, lalu pahami dengan objektif, dan temukan dengan jujur apakah agama anda sejalan dengan sains atau malah berbenturan.
Jangan anda berlelah-lelah berusaha mencocok-cocokkan agama teistik yang tertutup anda dengan sains. Agama anda ya agama anda, dan sains ya sains. Keduanya punya wilayah kewenangan masing-masing yang tidak perlu dicampuraduk atau dikumpulkerbaukan.
Hanya jika anda setuju dengan ide Einstein tentang agama kosmik sebagai agama masa depan, barulah anda punya harapan untuk mempertemukan ilmu pengetahuan dengan agama.
Dan ketahuilah juga bahwa bukan hanya Einstein pada masanya yang memikirkan agama semacam ini.
Dalam zaman kita, sosiolog agama yang terkenal, Robert N. Bellah, juga memikirkan hal yang serupa ketika dia belum lama ini mengajukan idenya tentang “religious naturalism”: melepaskan agama-agama dari referensi-referensi ke dunia supernatural, mengganti semuanya dengan referensi-referensi natural sehingga agama-agama dapat mengambil pandangan-pandangan sains modern dan mengungkapkan pandangan-pandangan sains ini dalam bahasa keagamaan yang sepenuhnya natural, sesuai dengan bahasa sains juga.
Hanya dengan pendekatan naturalisme religius ini, perang kebudayaan antara agama dan sains modern, kata Bellah, akan dapat diakhiri./39/
Bagaimanapun juga, jika anda mau beragama dengan cerdas, anda tidak bisa lagi menutup mata anda terhadap sains modern yang terus berkembang dan makin maju, dan anda perlu merumuskan kembali agama anda dengan memakai sains modern sebagai matriksnya atau sebagai rahimnya― inilah juga yang dimaksudkan Einstein sebagai agama kosmik.
Enam dasawarsa setelah Einstein, sehubungan dengan Buddhisme sosok agung Dalai Lama XIV menyatakan bahwa jika Buddhisme kedapatan tidak sejalan lagi dengan sains modern, Buddhisme harus segera disusun ulang. Katanya,
“Jika sains membuktikan kepercayaan-kepercayaan Buddhisme salah, maka Buddhisme akan harus diubah. Hemat saya, sains dan Buddhisme sama-sama mencari kebenaran dan berusaha memahami realitas. Dengan belajar dari pemahaman yang lebih maju dari sains tentang aspek-aspek realitas, saya percaya Buddhisme akan memperkaya pandangan dunianya sendiri.”/40/
Adakah sosok agung dalam agama anda sendiri yang telah atau akan menyatakan hal yang sama sehubungan dengan agama anda sendiri?
Jika ada, bergabunglah dengannya. Jika tidak ada, andalah yang perlu ambil inisiatif untuk melaksanakannya. Orang-orang masa depan lahir dari masa depan.
Jakarta, 11 Juni 2012
Ioanes Rakhmat
Editing mutakhir 4 Juni 2018
Catatan-catatan
/1/ Lihat wawancara oleh Deborah Solomon, “The Science of Second-Guessing”,
The New York Times Magazine, 12 December 2004,
http://www.nytimes.com/2004/12/12/magazine/12QUESTIONS.html?_r=0.
/2/ Video Discovery Channel Curiosity SO1EO1,
Did God Create the Universe? Compelling Explanations, tayangan perdana 7 Agustus 2011,
http://youtu.be/fmYlbqtAYOQ. Lihat penggalannya di video Youtube “Stephen Hawking There Is No God. There Is No Fate”
http://youtu.be/7L7VTdzuY7Y. Video yang sama yang terpasang utuh (42 menit 28 detik), dapat diperoleh di sini
http://www.dailymotion.com/video/xmc55o_curiosity-s01e01-did-god-create-the-universe_tech.
/3/ Lihat kolom Alan Boyle, “‘I’am an Atheist’: Stephen Hawking on God and Space Travel”,
NBCNews, 24 September 2014,
http://www.nbcnews.com/science/space/im-atheist-stephen-hawking-god-space-travel-n210076. Lihat juga kolom Chris Matyszczyk, “Stephen Hawking makes it clear: There is no God”,
CNET, 26 September 2014,
http://www.cnet.com/news/stephen-hawking-makes-it-clear-there-is-no-god/. Teks lengkap wawancara Hawking dengan
El Mundo lihat Pablo Jáuregui, ‘No hay ningún dios. Soy ateo’,
El Mundo, 26 Oktober 2014,
http://www.elmundo.es/ciencia/2014/09/21/541dbc12ca474104078b4577.html.
/4/ Video Discovery Channel Curiosity SO1EO1,
Did God Create the Universe? Compelling Explanations, tayangan perdana 7 Agustus 2011,
http://youtu.be/fmYlbqtAYOQ.
/5/ Deborah Solomon, “The Science of Second-Guessing”,
The New York Times Magazine, 12 December 2004.
/6/ Saksikan video youtube berjudul “Into the Universe With Stephen Hawking―Season 1 Full”,
http://youtu.be/4GcmbFb8afQ. Pernyataan ini juga diucapkan Hawking pada awal video Discovery Channel
Curiosity SO1EO1,
Did God Create the Universe? Compelling Explanations, tayangan perdana 7 Agustus 2011.
/7/ Deborah Solomon, “The Science of Second-Guessing”,
The New York Times Magazine, 12 December 2004.
/8/ Dennis O‘Shea, “Big Black Holes Can Block New Stars”,
John Hopkins University, 21 October 2014,
http://releases.jhu.edu/2014/10/21/starmaking-shutdown/. Selengkapnya kajian ini dimuat dalam jurnal
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), vol. 445, Issue 1, 21 November 2014, hlm. 460-478. Terbit online pertama kali 29 September 2014.
/9/ Lihat reportase “Astronomers find five supermassive black holes”,
RTE News, 6 July 2015,
http://www.rte.ie/news/2015/0706/713000-astronomers-find-five-supermassive-black-holes/.
/10/ Lihat Stephen Hawking, “Information Preservation and Wheather Forecasting for Black Holes”,
Cornell University Library, 22 January 2014,
http://arxiv.org/abs/1401.5761. Untuk uraian tentang Apparent Horizon yang digagas Stephen Hawking, lihat Zeeya Merali, “Stephen Hawking: ‘There are no black holes’”,
Nature, 24 January 2014,
http://www.nature.com/news/stephen-hawking-there-are-no-black-holes-1.14583.
/11/ Lihat reportase Nick Clark, “Stephen Hawking: Agression could destroy us”,
The Independent, 19 February 2015,
http://www.independent.co.uk/news/science/stephen-hawking-aggression-could-destroy-us-10057658.html. Lihat juga Ed Mazza, “Stephen Hawking Warns That Agression Could ‘Destroy Us All’”,
HuffingtonPost Science, 23 February 2015,
http://www.huffingtonpost.com/2015/02/23/stephen-hawking-aggression_n_6733584.html.
/12/ Ioanes Rakhmat, “Apakah Tuhan itu ada? Sebuah jawaban ilmiah kepada para ateis?”,
Freethinker Blog, 12 Agustus 2014, editing mutakhir 5 Maret 2016,
https://ioanesrakhmat.blogspot.co.id/2014/08/apakah-tuhan-itu-ada.html?m=0.
/13/ Tentang kemungkinan-kemungkinan yang tersedia untuk bisa mengadakan perjalanan lintas-waktu (
time travel), lihat uraian Stephen Hawking, “Stephen Hawking: How to build a time machine”,
MailOnline, 27 April 2010,
http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1269288/STEPHEN-HAWKING-How-build-time-machine.html.
/14/ Albert Einstein, “Religion and Science”,
New York Times Magazine, 9 November 1930; juga idem,
Ideas and Opinions (1954).
/15/ Helen Dukas dan Banesh Hoffman, eds.,
Albert Einstein: The Human Side (Princeton: Princeton University Press, 1954, 1981), hlm. 43 (“Letter to an atheist”, 24 March 1954).
/16/ Helen Dukas dan Banesh Hoffman, eds.,
Albert Einstein: The Human Side (Princeton: Princeton University Press, 1954, 1981), hlm.39.
/17/ Albert Einstein,
The World As I See It (New York: Philosophical Library, 1949), hlm. ??
/18/ Martin Gardner,
The Night Is Large: Collected Essays 1938-1995 (1996), hlm. 430.
/19/ Lihat reportase “‘Dear Einstein, Do Scientists Pray?’ Asks Sixth Grader―See His Amazing Response”,
HuffingtonPost 30 January 2014,
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/30/einstein-scientists-pray_n_4697814.html. Mengenai korespondensi Einstein dengan anak-anak, lihat Alice Calaprice, ed.,
Dear Professor Einstein: Albert Einstein’s Letters to and from Children. Pengantar oleh Evelyn Einstein (Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2002).
/20/ Helen Dukas dan Banesh Hoffman, eds.,
Albert Einstein: The Human Side (Princeton: Princeton University Press, 1954, 1981), hlm. 66.
/21/ John Adams,
Risk (London: University College London Press, 1995), hlm. 17.
/22/ Lihat berita “Einstein letter calls Bible ‘pretty childish’”,
NBCNews. Associated Press,
http://www.msnbc.msn.com/id/24598856/ns/us_news-faith/t/einstein-letter-calls-bible-pretty-childish/. Lihat juga Alice Calaprice,
The Ultimate Quotable Einstein (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2011), hlm. 342.
/23/ Walter Isaacson,
Einstein: His Life and Universe (New York: Simon and Schuster, 2008), hlm. 388-389. Pernyataan Einstein ini, yang ditulisnya 24 April 1929, adalah jawabannya kepada Rabbi Herbert S. Goldstein di kota New York yang, lewat sebuah telegram, bertanya kepadanya apakah dia percaya kepada Allah. Einstein diminta menjawab dalam 50 kata; tetapi Einstein cukup menjawabnya hanya dalam 27 kata (dalam bahasa Jerman). Lihat juga arsip reportase “Einstein believed in ‘Spinoza’s God’”,
New York Times, 25 April 1929,
https://mobile.nytimes.com/1929/04/25/archives/einstein-believes-in-spinozas-god-scientist-defines-his-faith-in.html.
/24/ Banesh Hoffmann, ed.,
Albert Einstein: Creator and Rebel (New York: New American Library, 1972), hlm. 95.
/25/ Alice Calaprice,
The Einstein Almanac (Baltimore: JHU Press, 2005), hlm. 91.
/26/ Albert Einstein, “Religion and Science”,
New York Times Magazine, Nov 9, 1930, hlm. 1-4. Lihat
http://www.sacred-texts.com/aor/einstein/einsci.htm.
/27/ William Hermanns,
Einstein and the Poet: In Search of the Cosmic Man (Brookline Village MA: Branden Books, 1983), hlm. 60.
/28/ Albert Einstein, “Religion and Science”,
New York Times Magazine, Nov 9, 1930, hlm. 1-4. Lihat
http://www.sacred-texts.com/aor/einstein/einsci.htm.
/29/ Albert Einstein, obituari dalam
New York Times, April 19, 1955. Lihat juga George Seldes,
The Great Thoughts (New York: Ballantine Books, 1996), hlm. 134.
/30/ Albert Einstein,
The World as I See It (Secaucus, NJ: Citadel Press, 1999), hlm. 5.
/31/ Helen Dukas dan Banesh Hoffman, eds.,
Albert Einstein: The Human Side (Princeton: Princeton University Press, 1954, 1981), hlm.39.
/32/ Albert Einstein, “Religion and Science” dalam
New York Time Magazine, November 9, 1930, hlm. 3-4. Lihat juga Alice Calaprice,
The Expanded Quotable Einstein (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 216.
/33/ Helen Dukas dan Banesh Hoffman, eds.,
Albert Einstein: The Human Side (Princeton: Princeton University Press, 1954, 1981), hlm. 95. Lihat juga surat Einstein, “Letter to a Brooklyn Minister”, 20 November 1950.
/34/ George Sylvester Viereck,
Glimpses of the Great (Duckworth, 1930), hlm. 372-373.
/35/ Walter Isaacson,
Einstein: His Life and Universe (New York: Simon and Schuster, 2008), hlm. 390.
/36/ Prinz Hubertus zu Löwenstein,
Towards the Further Shore (London: Victor Gollancz, 1968), hlm. 156. Lihat juga Walter Isaacson,
Einstein: His Life and Universe, hlm. 389. Ronald W. Clark,
Einstein: The Life and Times (New York: World Publishing Company, 1971), hlm. 425. Max Jammer,
Einstein and Religion: Physics and Theology (Princeton: Princeton University Press, 2002), hlm. 97.
/37/ Max Jammer,
Einstein and Religion: Physics and Theology, hlm. 97. Lihat juga Walter Isaacson, “Einstein and Faith”,
Time 169: 47, 5 April 2007. Pernyataan Einstein ini disampaikan ke seseorang yang tidak disebutkan namanya olehnya pada 7 Agustus 1941 (lihat
Einstein Archive, reel 54-927). Untuk memudahkan anda terfokus pada pandangan Einstein terhadap orang ateis, saya telah memotong bagian-bagian lain dari ucapannya ini yang tidak relevan.
/38/ Max Jammer,
Einstein and Religion: Physics and Theology, hlm. 51.
/39/ Robert N. Bellah,
Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age (Cambridge/London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2011), hlm. 97-104. Ringkasan buku tebal ini (744 halaman) sudah saya buat, termuat dalam buku saya
Beragama dalam Era Sains Modern (Jakarta: Pustaka Surya Daun, 2013), Lampiran 2, hlm. 437-442.
/40/ Tenzin Giyatso, “Our faith in science”,
The New York Times, 12 November 2005,
http://www.nytimes.com/2005/11/12/opinion/12dalai.html?pagewanted=all&_r=0.